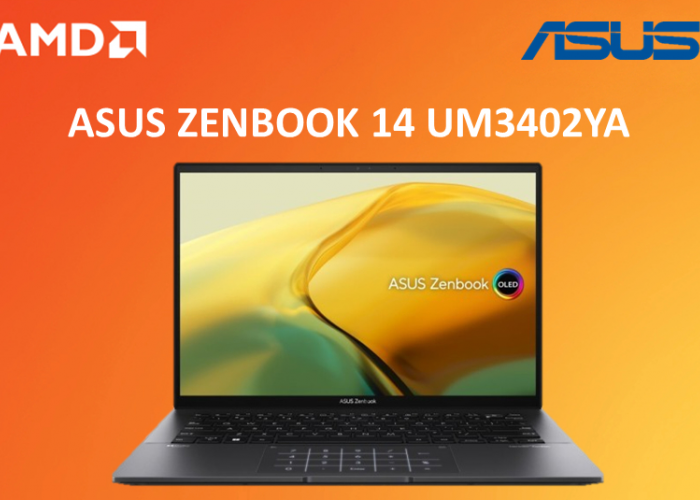Pengepungan di Bukit Duri dan Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia

Pengepungan di Bukit Duri dan Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia-net-
Film ini, yang dalam bahasa Inggris berjudul "The Siege Thorn High," berkisar pada kisah seorang guru seni bernama Edwin (diperankan oleh Morgan Oey) yang mengajar di SMA Bukit Duri, sebuah sekolah yang terletak di kawasan Jakarta Timur dan dihuni oleh murid-murid yang terbuang.
Edwin terpaksa berhadapan dengan Jefri (diperankan oleh Omara Esteghlal), seorang murid yang bengis dan menjadi ketua geng. Dalam situasi terjepit di dalam gedung sekolah, Edwin berjuang antara hidup dan mati.
Bertema thriller-action, "Pengepungan di Bukit Duri" dianggap oleh sebagian kalangan lebih mengerikan daripada film horor karena menampilkan perilaku manusia yang menyerupai kejahatan iblis. Di awal film, penonton disuguhkan dengan gambaran kerusuhan, penjarahan, serta kekerasan fisik dan mental yang dialami oleh etnis Tionghoa.
Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, adegan-adegan tersebut mencerminkan peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Visualisasi momen tersebut disajikan secara detail, seolah bercerita lewat tulisan, serta terekam di antara tembok-tembok yang lusuh.
Oleh karena itu, Joko Anwar, sang sutradara, memberikan peringatan konten atau trigger warning bagi para penonton. Ini disebabkan oleh adanya elemen kekerasan dan ketegangan rasial dalam cerita yang dapat memicu trauma bagi sebagian orang.
Penonton akan diajak merasakan roller coaster emosi sepanjang film. Namun, "Pengepungan di Bukit Duri" tetap dapat dinikmati tanpa perlu memikirkan teori-teori rumit seperti yang ada dalam film horor Joko Anwar sebelumnya. Di beberapa adegan, terdapat sentuhan komedi yang berhasil meredakan ketegangan yang ada.
Kedua pemeran utama, Omara dan Morgan, berhasil menyuguhkan akting yang memukau. Dalam beberapa adegan tanpa dialog, sorotan mata Omara seakan mampu "berbicara" dengan sendirinya. Joko Anwar berhasil menciptakan karakter yang kuat dalam sosok Jefri melalui penampilan Omara, hingga penonton dapat mengenal Jefri hanya melalui sajian visual yang disuguhkan.
Pemeran pendukung juga menunjukkan penampilan yang mengesankan, salah satunya adalah Satine Zanita yang berperan sebagai satu-satunya murid perempuan dalam geng Jefri.
Di awal film, "Pengepungan di Bukit Duri" memang terasa menakutkan dan berani membuka luka lama. Amarah dan kesedihan seolah membuncah saat membayangkan diri sebagai korban kekerasan. Joko Anwar pun mengangkat isu penting mengenai kondisi dunia pendidikan di Indonesia.
Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa
Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah kekerasan terhadap etnis Tionghoa, yang menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di Twitter/X.
Kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era kolonial. Masih ingatkah Anda dengan peristiwa tragis pada bulan Oktober 1740 yang dikenal sebagai pembantaian etnis Tionghoa di Kali Angke, Batavia?
Peristiwa itu dipicu oleh penyebaran wabah malaria yang melanda Batavia pada 1730-an, yang menyebabkan ribuan orang meninggal, termasuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk van Cloon. Masyarakat Tionghoa di Batavia dituduh sebagai pembawa wabah tersebut.
Pada 25 Juli 1740, dikeluarkan dekrit oleh Komisaris Urusan Pribumi, Roy Ferdinand, atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Adriaan Valckenier. Dekrit tersebut menegaskan bahwa orang-orang Tionghoa yang dianggap mencurigakan akan dideportasi ke Sri Lanka untuk memanen kayu manis di sana.
Dekrit tersebut digunakan oleh sejumlah pejabat Belanda untuk memeras komunitas Tionghoa yang kaya dengan ancaman deportasi jika mereka tidak membayar. Muncul pula isu yang mengklaim bahwa orang-orang yang dibawa ke Sri Lanka sebenarnya tidak sampai ke tujuan, melainkan dibuang ke tengah laut.
Isu ini memicu kemarahan di kalangan komunitas Tionghoa di Batavia. Situasi semakin memanas. Pada tanggal 7 Oktober 1740, sekelompok ratusan orang Tionghoa dan pribumi menyerang sebuah benteng pertahanan milik Belanda di Tanah Abang, yang mengakibatkan 50 orang tewas.
Sebagai respons, pemerintah kolonial mengirimkan pasukan berjumlah 1. 800 prajurit VOC yang dipimpin oleh Gustaaf Willem van Imhoff. Keesokan harinya, pasukan Belanda berhasil mengecoh serangan dari sekitar 10. 000 orang Tionghoa yang datang dari Tangerang dan sekitarnya. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya 1. 700 orang Tionghoa terkorbankan.
Seiring dengan itu, desas-desus mulai menyebar di antara kelompok etnis lain di Batavia, termasuk budak dari Bali serta pasukan Sulawesi, Bugis, dan Bali, yang menyatakan bahwa orang Tionghoa berencana untuk membunuh, memperkosa, atau memperbudak mereka. Akibatnya, rumah-rumah milik etnis Tionghoa dibakar di sepanjang Kali Besar.
Tentara VOC juga melancarkan serangan terhadap pemukiman Tionghoa di berbagai tempat di Batavia, di mana mereka membakar rumah dan menewaskan banyak orang. Dalam serangan berlangsung selama dua minggu tersebut, diperkirakan sekitar 10 ribu orang tewas dalam pembantaian Batavia tahun 1740, termasuk 500 tahanan dan pasien rumah sakit.
Kekerasan terhadap etnis Tionghoa kembali terjadi pada masa Orde Lama. Pada tahun 1954, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) didirikan dengan tujuan mengatasi permasalahan etnis Tionghoa melalui integrasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun bukan partai politik, Baperki sempat berpartisipasi dalam pemilu pertama pada tahun 1955. Memasuki paruh kedua abad ke-20, Baperki cenderung condong ke kiri dan akhirnya terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Isu mengenai keterlibatan pemerintah Cina dalam peristiwa tersebut beredar, dan menyusul pembekuan hubungan diplomatik antara kedua negara, kerusuhan anti-Cina semakin meningkat di seluruh negeri. Sekolah-sekolah Tionghoa ditutup, sementara bahasa dan tradisi mereka dilarang. Sekali lagi, orang Indonesia Tionghoa harus melewati masa-masa kelam.
Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tidak berhenti di era Orde Baru, malah semakin terlihat jelas. Mereka dilarang merayakan Imlek dan atribut-atribut terkait budaya Tionghoa mengalami pengurangan keberadaannya. Puncaknya terjadi dalam kerusuhan rasial pada tahun 1998.
Kerusuhan Mei 1998 adalah kejadian massal yang diwarnai demonstrasi anti-pemerintah serta penjarahan di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Solo. Salah satu kelompok yang paling terpukul dalam kerusuhan ini adalah keturunan Tionghoa, yang tidak hanya mengalami penjarahan tetapi juga menjadi korban pemerkosaan massal.
Menurut data, lebih dari seribu orang kehilangan nyawa dalam kerusuhan itu, termasuk sedikitnya 168 kasus pemerkosaan, serta kerugian akibat penjarahan mencapai Rp3,1 triliun. Banyak toko di Jakarta, Medan, dan Solo yang terbakar habis dalam kerusuhan ini.
Salah satu korban dari kekerasan massal di tahun 1998 adalah aktivis HAM bernama Ita Martadinata Haryono. Ita, yang saat itu masih duduk di bangku SMA, diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Hingga kini, pelaku dari tindakan kejam tersebut masih belum teridentifikasi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: